KEMARIN. Oke, ini tulisan aku buat ketika mendapat tugas kuliah, kalau tidak salah penulisan humas atau semacamnya. Udah lupa.
Singkatnya, kami satu kelas disuruh menonton film Di Balik Frekuensi bersama-sama, lalu menuliskan ulang pengalaman menonton pada sebuah blog. Taraaaa... terbitlah review-review-an Di Balik Frekuensi alakadarnya yang aku buat demi mendapat nilai A.
Saat mulai membangun Bengkuring Bakery Street di tahun 2016, tulisan ini aku hapus karena sangat-sangat tidak menjual. Namun, sewaktu ngobrol asyik dengan seorang kawan, dia mengungkapkan kalau dari semua tulisan yang pernah aku bikin, cerita tentang Di Balik Frekuensi adalah yang terbaik dan terfavorit serta ter-ter yang lain.
Berlagak so cool, padahal salang tingkah ditambah sumringah, aku cuman bisa bilang: Oh.
Well, tanpa ada kata, frasa, dan kalimat yang diganti, serta mencarinya sulit sekali karena harus membuka folder zaman kuliah satu-satu, inilah Pengalaman Menonton Film Di Balik Frekuensi.
 |
| Source: netizen |
***
Jika
diberi dua pilihan, antara menonton film kartun atau film dokumentar, pastilah
saya memilih film kartun. Tom and Jerry
misalnya, kisah konyol kucing dan tikus ini membuat saya tidak pernah bosan
menontonnya walaupun diulang berjuta-juta kali. Tapi berbeda dengan film Di
Balik Frekuensi. Film ber-genre dokumentar ini terlihat biasa saja seperti
film dokumentar lainnya pada saat intro.
Seiring berjalannya waktu, film ini
semakin asyik untuk ditonton. Scene to
scene Di Balik Frekuensi seperti menimbulkan magnet, di mana kita lengket di
bangkunya masing-masing untuk tetap setia menyaksikannya. Walaupun tak ada
adegan pukul-pukulan dengan stick golf,
film ini seakan menyihir saya untuk selalu ingin tahu apa yang akan terjadi
selanjutnya.
Prinsip
saya sebagai seorang Fan Boy, penyuka
karakter komik, seakan-akan luntur begitu saja ketika melihat Luviana, yang
menjadi tokoh utama pada Di Balik Frekuensi. Bagaimana tidak, perjuangan membela
haknya sebagai seorang jurnalis yang di non-aktifkan tanpa alasan, membuat saya ingin masuk ke dalam film
tersebut dan membantunya.
Ruangan gelap di Gedung Fakultas Kehutanan Universitas
Mulawarman terasa bergetar saat adegan Luviana bersama Aliansi Jurnalis Indonesia
(AJI) beramai-ramai mendatangi markas Partai Nasdem, yang di pimpin oleh
Surya Paloh yang sekaligus pemilik dari Metro TV, tempat Luviana bekerja. Bersatunya
Luvi dan AJI seperti Tony Stark yang bergabung bersama The Avengers demi menumpas kejahatan di muka bumi ini.
Di Balik Frekuensi dibuat dengan setting dan alur campur, artinya ada dua kisah dalam film
ini. Saya mengakui kalau film ini sangat berkesan dan menarik, namun kalau
boleh jujur, saya sempat tertidur beberapa detik ketika adegan Hari Suwandi
berjalan kaki dari Sidoarjo menuju Jakarta.
Alasan saya tidur bukan karena
bosan film ini tidak ada adegan perkelahian pria jantan, layaknya film-film Mel
Gibson. Tapi karena AC di Gedung Fahutan kebetulan sangat sejuk.
Mata saya
kembali tertuju ke layar besar, berukuran 4x4 meter. Aksi jalan kaki Hari Suwandi
ternyata mempunyai maksud menuntut pemerintah dan PT. Lapindo Brantas supaya melunasi
pembebasan lahan korban “Lumpur Lapindo”. Setelah 29 hari perjalanan, akhirnya
Hari Suwandi sampai di Jakarta, Ia pun menemui beberapa pejabat “Senayan” dan
megutarakan maksud kedatangannya.
Sementara
itu, negosiasi antara Luviana dan pemimpin Nasdem berakhir dengan senyuman. Tapi
di penghujung film, saya diberi kejutan dengan Luviana yang akhirnya di PHK.
Setelah negosisai dan perbincangan dramatis, yang disertai canda tawa, antara
Luviana dan Surya Paloh tersebut membuat saya berkata: KENAPA?
Diduga selama
bekerja di Metro TV, Luviana menginisiasi aliansi serikat pekerja. Kesedihan
saya yang seperti menonton film India semakin bertambah ketika Hari Suwandi
melakukan interview live di TV One. Secara gamblang dia mengatakan, keluarga Bakrie yang notabene-nya pemilik PT. Lapindo Brantas, mampu
mengatasi masalah tersebut. Hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disuarakan
sebelumnya. Kesan penjilat sangat pantas dilemparkan kepada Hari Suwandi.
Seandainya
saya bertemu dengan Hari Suwandi sekarang ini, sudah pasti saya akan memukul
kepalanya dengan kursi besi buatan Korea dan berharap kepalanya sembuh kembali
seperti ketika Tom menjahili Jerry. Namun saya sadar, kalau itu hanya bagian dari film, alhasil saya hanya bisa mengelus dada.
Lalu,
apa yang saya bisa didapat dari Di Balik Frekuensi?
Pertama, saya ingin
berterima kasih kepada Ucu Agustin, jika saya mempunyai sepuluh jempol, tentu
akan saya acungkan semua untuknya. Istilah dari Konglomerasi Media yang disampaikannya
melalui film ini sangat menyentuh dan menginformasikan kepada saya dunia
jurnalistik pada hari ini sangat membentuk pencitraan dari pemilik modal.
“Porsi
khusus” yang ditampilkan media-media besar, khususnya televisi sangat berpihak
pada pemilik modal. Media sebagai watch
dog seperti mengganti namanya sendiri menjadi suck dog. Media yang kita dambakan sebagai kontrol sosial hilang
begitu saja lantaran terpukau dengan rupiah yang berlipat ganda. Apakah kita
harus selalu menonton perkelahian kucing dan tikus yang tiada akhirnya atau
menonton media informasi yang terpaku pada 12 pemodal? Be smart, guys. (Hna)
***
Judul: Di Balik Frekuensi (2013)
Genre: Dokumentar
Sutradara: Ucu Agsutin
Judul: Di Balik Frekuensi (2013)
Genre: Dokumentar
Sutradara: Ucu Agsutin
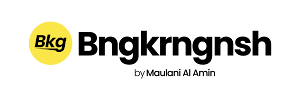


4 komentar